Editor : Ali Kadafi
Oleh: Sudarsono*
Sejarah politik manusia jarang memberi kejutan. Dari zaman kekaisaran hingga negara modern, satu pola terus berulang: kekuasaan yang tumbuh tanpa kontrol cenderung kehilangan batas moral. Ia tidak hanya menyimpang dalam urusan uang, tetapi juga mencari pembenaran atas hasrat—terutama melalui tubuh manusia.
Skandal seksual dan praktik korupsi karenanya bukan kecelakaan sejarah. Ia adalah konsekuensi logis dari relasi kuasa yang timpang, di mana jabatan publik diperlakukan sebagai hak istimewa, bukan amanah.
Isu perempuan yang belakangan menyeret nama Ridwan Kamil—entah yang telah dibantah, diuji secara hukum dan ilmiah, maupun yang masih menjadi spekulasi tidak seharusnya dipersempit sebagai gosip personal. Kasus semacam ini justru membuka ruang refleksi lebih luas tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana seks menjadi alat politik, serta bagaimana publik dan media membentuk penilaian moral terhadap elite.
Dalam konteks itu, Indonesia sesungguhnya hanya mengulang bab lama yang telah lama ditulis sejarah dunia.
Pemikir Prancis Michel Foucault, melalui The History of Sexuality, membongkar mitos bahwa seks adalah urusan pribadi semata. Seks, bagi Foucault, selalu berada dalam jaringan kuasa: diatur, diawasi, dan dimaknai oleh negara, agama, ilmu pengetahuan, serta norma sosial.
Tubuh manusia menjadi medan awal tempat kekuasaan menunjukkan dominasinya. Sejak Romawi Kuno, penguasa kerap menggunakan seks sebagai simbol supremasi. Nama-nama seperti Tiberius, Nero, dan Caligula dikenang bukan hanya karena kebijakan politik, tetapi juga karena skandal yang menunjukkan kaburnya batas antara otoritas publik dan nafsu pribadi.
Menariknya, hampir selalu ada irisan antara skandal seksual dan pembusukan institusi. Ketika hasrat dilegalkan oleh kuasa, kas negara pun sering ikut dijarah. Sejarah modern mencatat pola yang sama.
Kasus Bill Clinton dan Monica Lewinsky di Amerika Serikat tidak berhenti pada isu perselingkuhan. Ia menjelma menjadi krisis konstitusional akibat kebohongan di bawah sumpah jabatan. Literatur politik melihatnya sebagai contoh bagaimana kekuasaan eksekutif melahirkan ilusi kekebalan, hingga relasi kerja pun berubah menjadi relasi dominasi.
Italia menghadirkan contoh yang lebih vulgar melalui Silvio Berlusconi. Skandal pesta elite dan “bunga-bunga malam” berjalan beriringan dengan kasus korupsi, konflik kepentingan media, dan manipulasi hukum. Seks di sini bukan sekadar skandal, melainkan cermin budaya politik yang permisif terhadap penyalahgunaan kuasa.
Sementara itu, Dominique Strauss-Kahn, mantan Direktur IMF, memperlihatkan bagaimana posisi struktural dapat menciptakan relasi timpang bahkan sebelum pengadilan memutus benar atau salah. Tuduhan pelecehan seksual terhadap staf hotel menjadi pengingat bahwa kekuasaan global pun tidak imun dari problem etika.
Indonesia tidak berdiri di luar pola tersebut. Dari Orde Baru hingga era Reformasi, publik disuguhi rentetan kasus pejabat yang terjerat skandal moral dan korupsi secara bersamaan. Pejabat dengan perempuan simpanan yang difasilitasi negara, politisi yang mengalirkan dana publik untuk kepentingan pribadi, hingga tokoh agama dan pendidikan yang menyalahgunakan otoritas moral untuk eksploitasi seksual—semuanya menunjukkan satu benang merah.
Jabatan publik kerap dipahami keliru sebagai hak atas tubuh dan loyalitas orang lain.
Dalam kriminologi, fenomena ini dikenal sebagai abuse of entrusted power: kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani publik justru dipakai untuk memuaskan ego dan hasrat pribadi.
Dalam kerangka inilah, isu perempuan yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil perlu dibaca secara proporsional dan akademik. Media telah menyajikan beragam klaim, bantahan, klarifikasi hukum, hingga hasil pemeriksaan ilmiah. Namun yang lebih penting dari sekadar benar-salah individual adalah pertanyaan: mengapa isu ini begitu resonan di ruang publik?
Ridwan Kamil dikenal sebagai figur dengan modal karisma kuat—populer, komunikatif, dan merepresentasikan citra pemimpin modern. Max Weber menyebut bentuk ini sebagai otoritas karismatik: sangat efektif membangun dukungan, namun rapuh ketika legitimasi moralnya goyah.
Ketika karisma runtuh, kejatuhannya kerap lebih dramatis dibanding kekuasaan birokratik biasa. Di sinilah isu seks bekerja sebagai senjata delegitimasi paling ampuh.
John B. Thompson, dalam Political Scandal, menegaskan bahwa publik lebih mudah menghukum elite melalui skandal moral ketimbang melalui laporan kebijakan atau audit keuangan. Seks menjadi bahasa politik yang paling cepat dipahami massa.
Perbedaan utama antara skandal masa lalu dan hari ini terletak pada kecepatan. Media sosial membuat algoritma bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Nama, foto, dan potongan narasi menyebar tanpa konteks yang memadai.
Pierre Bourdieu menyebut media sebagai pemilik symbolic power—kekuatan untuk bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi membentuk realitas. Dalam kasus tokoh publik, media kerap beralih peran menjadi hakim moral, sementara publik berubah menjadi juri yang digerakkan emosi.
Risikonya bukan hanya fitnah, tetapi kaburnya batas antara etika publik dan penghakiman massal.
Psikologi kekuasaan menunjukkan bahwa mereka yang berada di puncak otoritas rentan mengalami moral disengagement. Muncul keyakinan bahwa aturan bisa dinegosiasikan, risiko dapat dikelola, dan reputasi bisa dilindungi jaringan kekuasaan.
Dari sinilah lahir dua skandal kembar: seks dan korupsi. Keduanya bersumber dari rasa superioritas struktural yang sama.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu mana pun. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Namun sejarah dan ilmu sosial memberi peringatan tegas: kekuasaan yang tidak dibatasi etika dan pengawasan hampir selalu mencari pelampiasan—dan tubuh manusia sering menjadi korban pertama.
Kasus Ridwan Kamil, sebagaimana banyak kasus lain di dunia dan Indonesia, seharusnya menjadi cermin kolektif, bukan sekadar konsumsi gosip. Demokrasi tidak cukup ditopang pemilu dan popularitas. Ia menuntut etika kekuasaan yang ketat, media yang bertanggung jawab, serta publik yang kritis namun adil.
Sejarah telah berkali-kali menuliskan pelajaran ini. Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita belajar darinya, atau terus mengulangnya dengan wajah dan nama baru?
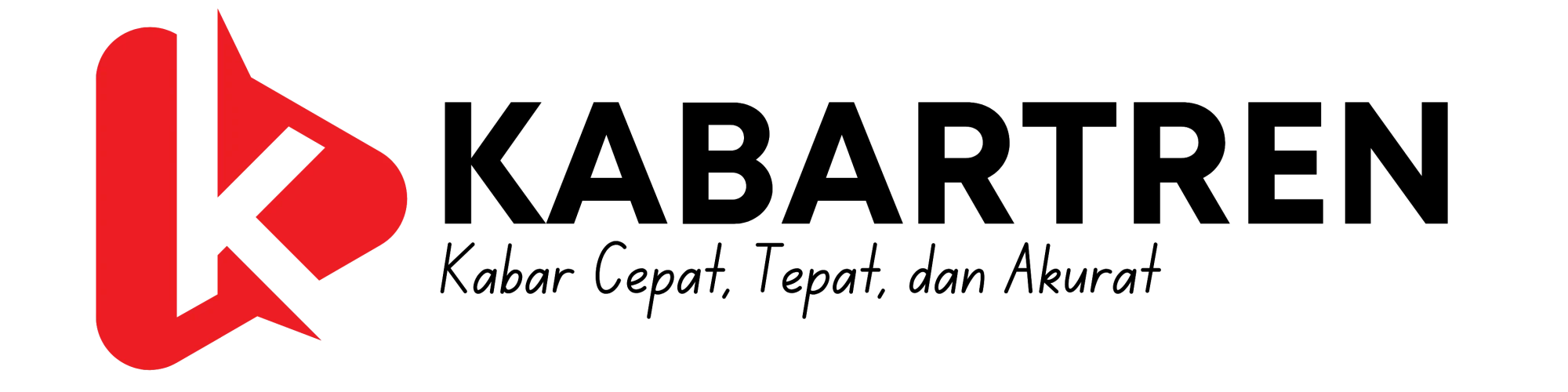
























Komentar