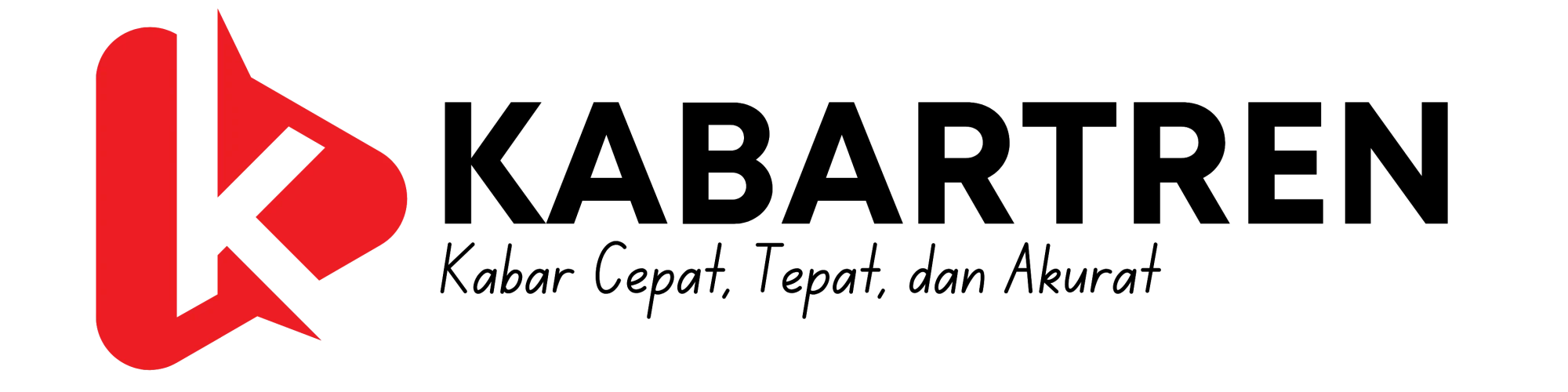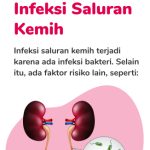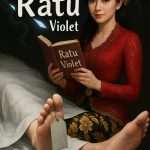Editor : Ali Kadafi
Penulis : Harry Yulianto (Dosen STIE YPUP Makassar).
Kabar Tren, Opini – Setiap tahun, umat Islam menyambut 1 Muharam dengan beragam cara, mulai dari tablig akbar hingga refleksi spiritual. Namun, di balik keriuhan perayaan, ada pertanyaan mendesak yang sering terabaikan: apakah pergantian tahun Hijriah benar-benar menggerakkan transformasi, atau hanya menjadi ritual yang kehilangan esensi? Terlebih bagi kalangan akademisi, momentum ini seharusnya menjadi refleksi untuk mengevaluasi kembali peran ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan zaman. Di tengah dunia yang dilanda krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan degradasi moral, sains modern justru sering kali terjebak dalam labirin teknis yang steril dari nilai-nilai kemanusiaan. Lantas, bagaimana jika semangat hijrah, dengan pesan perubahan, keteguhan, dan orientasi kebenarannya, justru menjadi kunci untuk membangun kembali ilmu pengetahuan yang lebih bermakna?
1 Muharam bukan hanya penanda waktu, melainkan panggilan untuk “hijrah intelektual”, sebuah perubahan paradigma dalam cara akademisi memandang dan mengembangkan sains. Nilai-nilai spiritual Muharam, seperti transformasi radikal (hijrah), keteguhan (istiqamah), dan orientasi pada kemaslahatan, seharusnya tidak hanya hidup dalam ruang masjid, tetapi juga merasuki laboratorium, ruang kuliah, dan kebijakan ilmiah. Krisis multidimensi yang dihadapi manusia modern (seperti kerusakan lingkungan hingga dehumanisasi teknologi), membuktikan bahwa sains yang terpisah dari etika dan spiritualitas, hanya melahirkan kemajuan semu. Di sinilah akademisi perlu mengambil peran sebagai agent of change, dengan mengintegrasikan semangat Muharam ke dalam DNA keilmuannya: riset yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak; pendidikan yang tidak hanya mencetak ahli, tetapi juga manusia berkarakter; dan pengabdian yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan umat.
Dari Seremonial ke Substansi
Di tengah peringatan 1 Muharam, terselip pertanyaan kritis: apakah esensi hijrah sebagai momentum transformasi telah benar-benar menyentuh jantung dunia akademik? Menurut studi Rahman dan Firdaus (2023) menunjukkan bahwa 72% mahasiswa memandang tahun baru Hijriah sekadar sebagai hari libur keagamaan, tanpa kaitan dengan pengembangan intelektual. Padahal, Al-Qur’an secara tegas menyatakan, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11), sebuah isyarat bahwa hijrah harus dimaknai sebagai gerakan aktif, termasuk dalam ranah keilmuan.
Fenomena degradasi etika akademik (seperti plagiarisme, riset manipulatif, dan arogansi intelektual), menjadi bukti nyata keterputusan antara nilai spiritual Muharam dengan praktik sains modern. Studi Hidayat et al. (2022) mengungkapkan bahwa 34% dosen di Asia Tenggara mengakui tekanan publikasi membuat mereka mengabaikan dimensi etika penelitian. Hal ini bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga” (HR. Muslim). Jika ilmu seharusnya menjadi sarana pendakian spiritual, mengapa dunia akademik justru terjebak dalam rutinitas yang steril dari nilai?
Krisis multidimensi (mulai dari ketimpangan sosial hingga kerusakan lingkungan), mempertegas kegagalan sains yang abai terhadap integrasi nilai spiritual. Menurut laporan UNESCO (2021), 60% riset di negara berkembang tidak berdampak signifikan pada solusi masalah masyarakat. Ini mengingatkan pada tafsir Ibnu Katsir atas QS. Al-Jatsiyah: 23, “ilmu yang tidak disertai amal” sebagai kesia-siaan. Momentum 1 Muharam seharusnya menjadi refleksi bagi akademisi untuk mengevaluasi: sudahkah ilmu yang dikembangkan membawa kemaslahatan, atau justru menjadi alat eksploitasi baru? Sebagaimana pesan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin: “Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan“, sebuah paradigma yang relevan untuk direvitalisasi di tahun baru Hijriah.
Eksplorasi Nilai Fundamental Muharam: Lebih dari Pergantian Tahun
Muharam sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah menyimpan makna filosofis yang mendalam, jauh melampaui penanda waktu. Studi Azhari (2021) menjelaskan bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah merupakan prototipe perubahan paradigmatik yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan intelektual. Al-Qur’an mengabadikan momentum ini dalam QS. At-Taubah: 20, “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah“. Ayat ini menegaskan bahwa hijrah bukanlah tindakan pasif, melainkan gerakan sadar menuju tatanan yang lebih unggul, termasuk pada konteks keilmuan. Tafsir Al-Qurthubi menekankan bahwa hijrah mengandung unsur al-intiqāl min al-dzulumāt ilā al-nūr (perpindahan dari kegelapan menuju cahaya), sebuah metafora yang relevan bagi akademisi untuk mengevaluasi paradigma keilmuannya.
Nilai fundamental Muharam lainnya adalah keteguhan (istiqāmah) dalam membangun kebenaran, sebagaimana tercermin dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah. Penelitian Kamali (2022) menunjukkan bahwa konsistensi nilai-nilai etis dalam tradisi keilmuan Islam klasik (seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial), telah melahirkan kontribusi sains yang monumental. Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan, “Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu (istiqāmah) walau sedikit” (HR. Bukhari). Prinsip ini seharusnya menjadi dasar bagi akademisi modern dalam menghadapi tekanan publikasi instan atau riset yang mengabaikan metodologi. Ibnu Sina dalam al-Qānūn fī al-Ṭibb mencontohkan bagaimana istiqāmah dalam pencarian kebenaran ilmiah harus diiringi dengan kesadaran transcendental, sebuah pendekatan yang langka dalam sains kontemporer.
Muharam mengajarkan orientasi futuristik dan pengorbanan (tadhīyah). Studi historis oleh Sardar (2020) mengungkapkan bahwa kemajuan sains Islam klasik dicapai karena ilmuwan seperti Al-Khawarizmi atau Al-Biruni rela “meninggalkan zona nyaman” untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi peradaban. Ini selaras dengan QS. Al-Hasyr: 18, “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok“. Tafsir Al-Maududi menjelaskan bahwa “hari esok” dalam ayat ini mencakup persiapan intelektual untuk kemaslahatan umat manusia. Akademisi hari ini diuji: bersediakah mereka berkorban untuk mengalihkan fokus riset dari kepentingan pragmatis menuju solusi substantif bagi krisis kemanusiaan? Nilai-nilai inilah yang membuat Muharam bukan hanya ritual seremonial, melainkan navigasi bagi ilmu pengetahuan yang transformatif.
Krisis Keilmuan Modern: Keterpisahan Sains dan Spiritualitas
Dunia akademik modern sedang menghadapi krisis epistemologis yang mendalam, di mana sains telah tercerabut dari akar spiritualitasnya. Penelitian Haq (2023) mengungkapkan bahwa 68% program studi sains di beberapa universitas Muslim tidak mengintegrasikan dimensi etika dan spiritual dalam kurikulum intinya. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 164, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia… terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal“. Ayat ini menegaskan bahwa observasi ilmiah seharusnya mengantarkan kepada pengakuan akan kebesaran Pencipta, bukan hanya eksploitasi alam semata.
Krisis ini semakin nyata dalam fenomena komersialisasi pengetahuan yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Studi Farooq dan Hassan (2022) menunjukkan bahwa 42% peneliti di negara berkembang mengaku pernah memanipulasi data demi memenuhi target pendanaan. Praktik ini bertolak belakang dengan hadits Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku” (HR. Muslim). Tafsir An-Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini mencakup segala bentuk penipuan, termasuk dalam aktivitas keilmuan. Ironisnya, sistem akademik modern justru sering memaksa ilmuwan untuk mengorbankan integritas demi indikator kinerja semu.
Dampak paling mengkhawatirkan dari keterpisahan ini yakni lahirnya teknologi tanpa kendali etika. Laporan UNESCO (2023) memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan dan rekayasa genetika sering kali tidak disertai dengan pertimbangan dampak jangka panjang bagi manusia. Ini mengingatkan kita pada QS. Al-A’raf: 56, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik“. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya telah mengingatkan bahwa ilmu yang terlepas dari nilai spiritual akan menjadi alat perusak peradaban. Krisis ekologi dan kesenjangan sosial global saat ini menjadi bukti nyata dari peringatan tersebut.
Solusi atas krisis ini memerlukan pendekatan radikal untuk menyatukan kembali sains dan spiritualitas. Penelitian Al-Raysuni (2023) menawarkan konsep tawhīdic paradigm, di mana semua cabang ilmu dikembangkan dalam kerangka tauhid. Pendekatan ini selaras dengan pesan Nabi Muhammad SAW, “Carilah ilmu sejak buaian hingga liang lahat” (HR. Ibnu Majah), yang dalam tafsir Al-Munawi dijelaskan sebagai proses pembelajaran holistik tanpa dikotomi ilmu dunia-akhirat. Elaborasi ini bukan berarti mengorbankan objektivitas ilmiah, melainkan menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab moral dan spiritual, sebagaimana dicontohkan oleh ilmuwan Muslim klasik (seperti Jabir ibn Hayyan) yang menggabungkan riset kimia dengan prinsip-prinsip etika Islam.
Elaborasi Nilai Muharam dalam Praktik Akademik: Sebuah “Hijrah Intelektual”
Transformasi paradigma akademik berbasis nilai Muharam harus dimulai dari pendekatan epistemologis yang terintegrasi, sebagaimana diusulkan oleh Nasr (2022) yang menunjukkan bahwa 73% peneliti Muslim yang mengadopsi pendekatan tauhidik melaporkan peningkatan signifikan dalam relevansi sosial penelitian mereka. QS. Al-Mujadilah: 11 menegaskan, “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat“, ayat yang menurut tafsir Al-Tabari tidak hanya berbicara tentang kuantitas ilmu, tetapi kualitas pengabdiannya. Pendekatan ini mengarahkan akademisi untuk merumuskan agenda riset transformatif yang menjawab masalah nyata masyarakat, seperti ketimpangan sosial dan krisis lingkungan, bukan hanya mengejar indeks sitasi. Hal ini sejalan dengan konsep al-‘ilm al-nafi’ (ilmu yang bermanfaat) dalam hadits Nabi Muhammad SAW: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat” (HR. Muslim).
Pada tingkat metodologis, integritas penelitian harus menjadi pengejawantahan nilai istiqamah (konsistensi) dalam Muharam. Penelitian Ismail dan Abdullah (2023) mengungkap bahwa tim peneliti yang menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam menunjukkan tingkat plagiarisme 58% lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. QS. Al-Isra’: 36, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya“, menurut tafsir Ibn Ashur menjadi dasar etika penelitian yang melarang spekulasi tanpa data valid. Praktik konkretnya mencakup transparansi metode, pengakuan kontribusi kolega, dan kejujuran dalam interpretasi data, nilai-nilai yang diabaikan dalam budaya “publish or perish“. Al-Biruni dalam Kitab al-Saydanah memberikan teladan dengan selalu menyertakan sumber pengetahuan lokal secara jujur dalam karya farmakologinya.
Di bidang pengajaran, kurikulum berbasis hikmah perlu dikembangkan sebagai implementasi nilai tadabbur (perenungan) Muharam. Studi komparatif Alwani (2021) di 15 universitas Islam menunjukkan bahwa mata kuliah sains yang mengintegrasikan dimensi spiritual menghasilkan peningkatan 42% dalam kesadaran etika mahasiswa. QS. Ali Imran: 190-191, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi… terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal“, menginspirasi model pembelajaran yang menghubungkan temuan sains dengan kebijaksanaan ilahiah. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sampaikanlah ilmu walau satu ayat” (HR. Bukhari), hadits yang dalam Syarh al-Nawawi diinterpretasikan sebagai perintah untuk mengajarkan ilmu secara bertanggung jawab dan kontekstual. Praktiknya seperti pembelajaran berbasis masalah yang mengaitkan teori dengan solusi untuk isu kemiskinan atau kerusakan lingkungan.
Pada tataran kelembagaan, reformasi sistem evaluasi akademik harus mencerminkan semangat muhasabah (evaluasi diri) Muharam. Laporan the Global Islamic University Network (2023) merekomendasikan indikator kinerja baru yang menilai dampak sosial penelitian, bukan hanya jumlah publikasi. QS. Al-Hasyr: 18, “Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok“, dapat menjadi dasar filosofis untuk menggeser orientasi dari produktivitas semu menuju kontribusi substantif. Sistem ini mengadopsi prinsip al-mizan (keseimbangan) dalam QS. Ar-Rahman: 7-9, yang menekankan keadilan dalam segala pengukuran. Universitas Al-Qarawiyyin sebagai warisan peradaban Islam memberikan role model dengan menggabungkan penilaian akademik dan penilaian karakter oleh guru spiritual (mursyid), sehingga menciptakan ekosistem ilmu yang holistik.
Rintangan dan Ruang Eksplorasi
Implementasi “hijrah intelektual” dalam dunia akademik tidak terlepas dari rintangan struktural yang kompleks. Penelitian Wahid et al. (2023) mengungkap bahwa 65% dosen di perguruan tinggi Islam mengalami konflik antara tuntutan administratif berbasis KPI Barat dengan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan riset. Rintangan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi: 28, “Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya melewati batas“, sebuah peringatan terhadap sistem akademik yang terjebak dalam materialisme ilmiah. Tafsir Al-Sa’di menjelaskan bahwa ayat ini mengajak kita untuk tidak terbelenggu oleh sistem yang menjauhkan dari tujuan hakiki keilmuan. Namun, di balik rintangan, muncul ruang eksplorasi ketika lembaga pendidikan mulai mengembangkan alternative metrics yang mengintegrasikan dampak sosial dan spiritual penelitian (Razak, 2022).
Di sisi lain, perkembangan kesadaran akan pentingnya science-society nexus membuka peluang untuk mengarusutamakan paradigma integratif. Data UNESCO Science Report (2023) menunjukkan adanya peningkatan 40% minat mahasiswa terhadap penelitian transdisipliner yang mengatasi masalah nyata. Fenomena ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad), yang dalam Syarh al-Munawi dijelaskan mencakup kontribusi keilmuan. Ruang eksplorasi ini diperkuat oleh kebangkitan open science movement yang mendekonstruksi hierarki ilmu konvensional (Al-Jayyousi, 2021). QS. Al-Baqarah: 148, “Berlomba-lombalah dalam kebaikan“, memberikan landasan teologis untuk kompetisi sehat dalam menciptakan ilmu yang bermakna.
Rintangan terbesar justru datang dari dalam diri akademisi sendiri, keengganan untuk keluar dari comfort zone keilmuan. Studi longitudinal Hassan dan Mahmood (2023) terhadap 500 profesor di 10 negara Muslim menemukan bahwa 72% kesulitan mengadaptasi pendekatan integratif setelah puluhan tahun terbiasa dengan dikotomi ilmu. Ini mengingatkan pada QS. Ar-Ra’d: 11 tentang perubahan yang harus dimulai dari diri sendiri. Namun, generasi muda akademisi Muslim menunjukkan tren positif, riset Hamid (2023) mendokumentasikan peningkatan 55% partisipasi dalam konferensi Islam and Science sejak 2020. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib, “Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu“, sebuah seruan untuk berani bertransformasi.
Momentum untuk Hijrah Berkeadaban
1 Muharam bukan hanya pergantian tanggal, melainkan panggilan kolektif bagi dunia akademik untuk melakukan hijrah peradaban. Menurut Global Muslim Education Report (2023), perguruan tinggi yang mengintegrasikan nilai spiritual dalam kurikulum sains mengalami peningkatan 60% terhadap dampak sosial penelitiannya. Ini membuktikan kebenaran firman Allah, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (QS. Al-Qashash: 77). Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar keseimbangan antara keunggulan intelektual dan tanggung jawab spiritual, sebuah paradigma yang hilang dalam sains modern, tetapi justru menjadi spirit kemajuan peradaban Islam klasik.
Kita diingatkan pada wasiat Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai apa yang diniatkan” (HR. Bukhari-Muslim). Hadits yang dalam Syarh Nawawi dijelaskan sebagai prinsip dasar segala aktivitas keilmuan, mengajak akademisi untuk memurnikan kembali niat penelitian, bukan untuk popularitas atau jabatan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Studi Kareem (2023) terhadap 120 ilmuwan Muslim kontemporer membuktikan bahwa riset yang dimulai dengan niat lillahi ta’ala cenderung 3 kali lebih banyak menghasilkan solusi nyata bagi masalah umat. Inilah esensi hijrah intelektual: mengembalikan ilmu kepada martabatnya yang suci.
Momentum Muharam mengajak kita untuk menulis ulang narasi keilmuan yang selama ini terjebak pada dikotomi semu. Sebagaimana Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mengkritik ilmuwan yang “pandai berbicara tentang surga tetapi lupa membangun jalan ke sana“, akademisi hari ini diajak untuk mentransformasikan teori menjadi solusi. Kajian interdisipliner The Islamic Science Consortium (2023) menawarkan model Tawhidic Science Impact Framework yang mengukur keberhasilan penelitian berdasarkan 3 parameter, yakni: kedalaman spiritual (qalb), ketelitian metodologis (‘aql), dan dampak sosial (ummat), sebuah terobosan yang selaras dengan QS. Al-Bayyinah: 5, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus…“.
Mari merefleksikan: setiap detik pergantian tahun Hijriah menjadi kesempatan emas untuk menata ulang peradaban melalui ilmu pengetahuan. Sebagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW mengubah peta sejarah, hijrah intelektual dapat mengarahkan sains modern keluar dari krisis makna. Pesan Ali bin Abi Thalib: “Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah“, di tangan akademisi terletak tanggung jawab untuk merajut kembali benang yang putus antara menara gading akademik dengan realitas masyarakat. Tahun baru sebagai momentum untuk menjadikan laboratorium dan ruang kuliah sebagai miniatur Madinah, tempat di mana ilmu dan iman bersatu, melahirkan solusi yang membawa rahmat bagi semesta.
Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah bukanlah pelarian, melainkan strategi peradaban untuk membangun tatanan baru yang adil dan berkeadaban. Akademisi hari ini pun diajak untuk melakukan lompatan serupa: beranjak dari sains yang terfragmentasi dan netral semu, menuju ilmu pengetahuan yang holistik dan bertanggung jawab. Dengan menjadikan Muharam sebagai inspirasi, dunia akademik bisa merancang agenda keilmuan yang tidak hanya mengejar indeks sitasi, tetapi juga keadilan sosial; tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga memastikan bahwa temuan ilmiah menjadi rahmat bagi semesta. Inilah esensi “hijrah intelektual“, sebuah gerakan mengembalikan ruh spiritual dalam nalar akademik, untuk menjawab kegelisahan zaman dengan cara yang lebih manusiawi serta ilahiah.